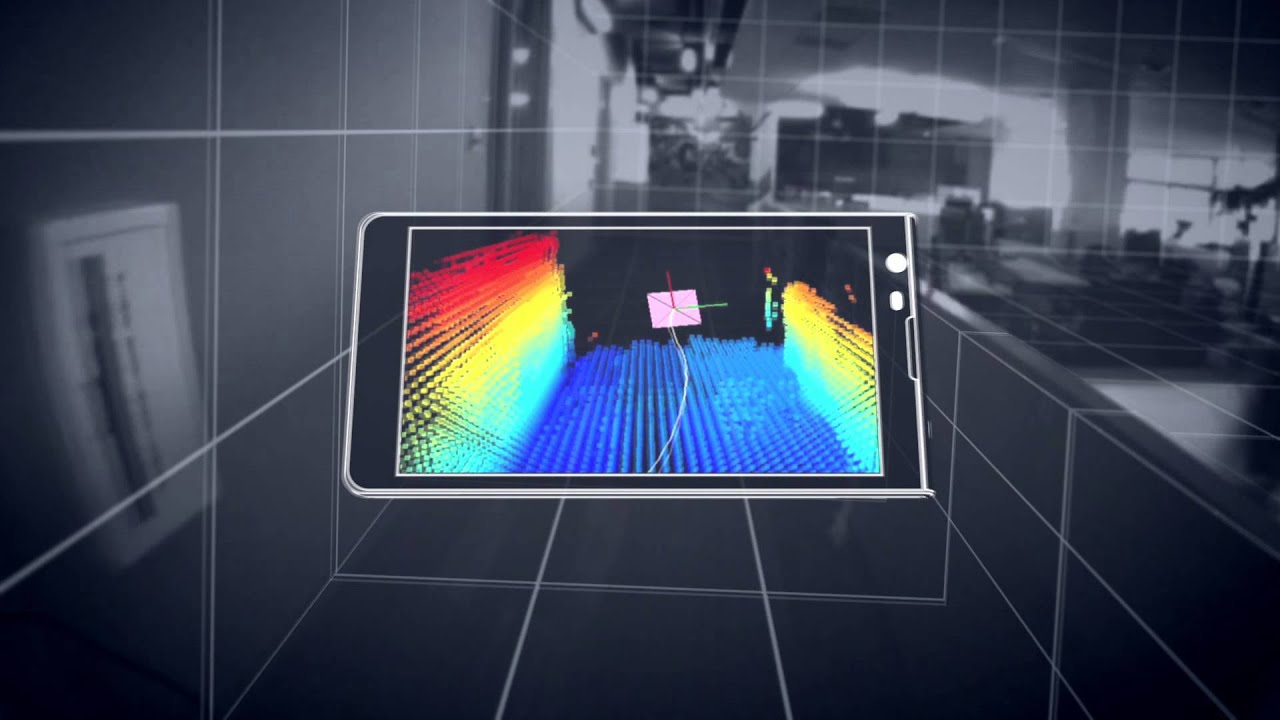Meski miskin,
mereka pantang meminta-minta. Katanya takut dimarahi leluhur. Hingga
kini masyarakat Kampung Naga enggan menembok rumahnya, tidak suka
televisi apalagi listrik, mobil maupun pakaian warna-warni. Mereka juga
menangis jika punya jabatan, katanya takut korupsi. Kehidupan duniawi,
bagi mereka, benar-benar tidak ada.
Begitu sarung-sarung dilemparkan ke tepi sungai, lebih dari seratus
lelaki tampak telanjang bulat. Berlarian mereka terjun ke Sungai Ciwulan
yang airnya cokelat. Menerjang arus di tengah serakan batu-batu besar,
tubuh mereka tampak tenggelam lalu muncul lagi di permukaan sungai yang
lebarnya sekitar 15 meter itu.
Mereka menggosok bagian badan di atas pusar dengan leuleueur, cairan
dari campuran akar dan buah tertentu. “Memakai sabun pada peristiwa ini
dilarang,” ujar seorang lelaki yang masih menggosok badannya dengan
cairan berwarna merah muda itu.
Setelah menyelam sekali lagi dan menggosok badan, kali ini tanpa
leuleueur, mereka naik ke darat. Tanpa mengeringkan badan, mereka pada
menyambar kain yang mereka campakkan tadi.
“Kami baru melakukan bebersih,” ujar Djadja Sutedja, 54 tahun, kuncen atau pemimpin adat di Kampung Naga.
Itu
merupakan awal rangkaian upacara hajat sasih, semacam penghormatan
kepada leluhur. Biasanya dilakukan enam kali setahun. Mereka sedianya
akan melangsukan upacara pada pekan ketiga bulan Maret, bertepatan
dengan pertengahan Jumadil Akhir.
Kampung di mana orang-orang berendam terletak di Desa Neglasari,
Kecamatan Salawu, 30 km dari Tasikmalaya dan 26 km dari Garut, Jawa
Barat. Namanya cukup unik: Kampung Naga.
Untuk bisa ke Kampung Naga, orang harus melewati sekitar 500 anak
tangga. Terbuat dari batu yang dilapis semen, tangga itu menuruni bukit
yang terjal dengan kemiringan sekitar 45 derajat.
Dari muara tangga terbentang jalan batu di antara sawah-sawah. Indah,
memang. Sungai Ciwulan, yang biasa digunakan untuk bersuci, mengalir di
sisi kampung sebelah utara hingga ke timur. Sedangkan di arah barat dan
timur, perbukitan yang dimanfaatkan untuk persawahan berdiri mengepung.
Selain 94 rumah penduduk, di kampung ini juga terdapat sebuah masjid, satu balai kampung, dan satu bangunan yang disebut.
Rumah pimpinan adat, kuncen, terletak di sebelah kiri masjid.
Sekeliling kampung dipagari bambu dan pepohonan lain, hingga batas
pinggirnya jelas kelihatan. Di tepi kolam-kolam ikan terdapat saung
lisung, tempat menumbuk padi, leuit, tempat menyimpan padi, serta
ruangan-ruangan kecil yang terbuat dari anyaman bambu dan dialiri air
pancuran, yang berfungsi sebagai kamar mandi, wc, dan tempat cuci
pakaian.
Tak ada penduduk yang punya kamar mandi pribadi. Ini uniknya. Di
sekitar kolam itu juga dibangun kandang kerbau atau kambing. Daerah ini
termasuk wilayah kotor, sedangkan daerah tempat tinggal dan bangunan
umum merupakan wilayah bersih.
Ini memang kampung orang Islam, yang kehidupan sehari-harinya akrab
dengan air (berwudu, mencuci najis, mandi), sehingga yang kotor dan yang
bersih memang tidak bercampur baur.
Kampung Naga memang unik dibanding kampung lain-lainnya. Di sini sekitar 335 orang tinggal. Mereka mengaku keturunan.
Konon, moyang ini dahulu prajurit Mataram yang malu pulang setelah gagal menyerbu Batavia pada zaman Sultan Agung.
Selain lebih dari 300 orang yang kini berdiam di dalam, ratusan
keturunan lainnya berada di luar kampung. Dan kelompok itu sendiri
mereka sebut, artinya sekampung Naga, seadat Naga.
Orang-orang Sa Naga terkenal sangat patuh memegang tradisi. Mereka
tidak suka bila listrik masuk desa. Bukan itu saja, mereka juga tidak
suka televisi. Mereka juga enggan menggunakan mobil. Mengenakan pakaian
warna-warni. Identiknya, mereka hanya menggunakan pakaian berwarna putih
atau hitam. Selain itu, sarung juga menjadi ciri khas mereka. Yang
menarik, semua orang di Kampung Naga tidak mengenakan alas kaki seperti
sandal atau sepatu.
“Kami selalu taat terhadap leluhur. Benda-benda modern selalu membawa
sial,” demikian diungkapkan Mak Loh, warga Kampung Naga paling tua.
Usianya mencapai 100 tahun.
Pada hajatan sasih ini, kata Mak Loh, semua orang memohon berkah agar diberi keselamatan dan rezeki yang cukup.
“Kami selalu taat kepada adat nenek moyang,” ujarnya, sambil mengunyah ikan emas dan nasi putih.
“Kepatuhan kami pada adat sangat tinggi,” ujar Mak Loh.
“Seminggu tiga hari kami melakukan upacara nyepi.” Waktu nyepi itu,
hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Biasanya kami membisu jika ditanya tentang
riwayat nenek moyang dan Kampung Naga.
Kepatuhan lain: “Kami tak berani menyebut Kecamatan Singaparna di Tasikmalaya.”
Sebab nama itu, lanjut Mak Loh, sama dengan nama leluhurnya. “Kami menyebut kecamatan itu Galunggung.”
Kenapa Kampung Naga tidak suka dengan benda-benda modern, karena
takut terkena kuwalat. Padahal, hanya sekitar 500 meter dari mereka
pengaruh peradaban modern sudah terasa. Jalan besar yang menghubungkan
Tasikmalaya dengan Garut itu setiap hari ramai dilewati kendaraan
bermotor yang memungkinkan orang melompat sekaligus ke kehidupan modern.
Pergi ke kota, paling tidak.
Sebaliknya, gaya hidup masyarakat Kampung Naga sangat tradisional
sekali. Mereka benar-benar menggunakan tradisi leluhur. Semua rumah
tidak ada yang terbuat dari tembok, pesawat televisi juga tidak ada,
apalagi mobil. Menurut mereka, kegairahan modern hanya akan membungkam
seseorang untuk menuruti syahwat duniawi.
“Kami mempunyai falsafah hidup,” ujar Mak Loh, yakni
Teu Saba, Teu Soba. Teu Banda, Teu Boga. Teu Weduk, Teu Bedas.
Teu Gagah, Teu Pinter.
Artinya: “Kami dianjurkan menjauhi kehidupan harta dan tidak merasa lebih dari yang lain,” katanya.
Soal urusan adat, Kampung Naga (kepala desa) Kasadayana (54)
mengatakan, dirinya sama sekali tidak berani meninggalkan adat yang ada.
Selain takut kuwalat, dia juga bilang hal itu sudah menjadi tradisi
yang terbantahkan.
Bersama puluhan lelaki Sa Naga yang lain, Kasadayana duduk bersila di
masjid yang terletak di tengah-tengah perkampungan. Dan seperti
orang-orang lain ia pun memakai jubah putih yang panjangnya sampai ke
lutut, menutup sebagian kain sarung pelekatnya.
“Seperti pada waktu mandi, memakai celana dalam sekarang juga tidak boleh,” ujarnya.
Masjid kampung Naga sendiri berukuran sekitar 5 x 10 meter. Bila
hajat sasih tiba, masjid itu tampak bernada putih oleh warna jubah
belacu yang dikenakan orang-orang. Mereka duduk bersila dan di depannya
tergeletak sapu lidi bertangkai kayu cukup panjang. Mereka menunggu saat
berangkat ke makam Eyang Singaparna yang terletak di pucuk bukit, hanya
sekitar satu kilometer dari masjid.
Benar, di barat rumah ibadah terdapat bangunan lain yang besar.
Berukuran 3 x 6 meter. Rumah beratap iju. Berdinding anyaman bambu yang
disebut, semacam potongan bambu yang dianyam berselang-seling horisontal
dan vertikal.
Sekeliling bangunan itu dipagari bambu. “Bangunan yang keramat memang selalu kami pagari bambu,” ujar Kasadayana.
Di latar belakang rumah besar itu tampak pohon-pohon tinggi dan rimbun. Bangunan yang disebut
Bumi Ageung
itu memang membersitkan misteri. Dan memang, di Bumi Ageung inilah
senjata pusaka Kampung Naga berupa tombak dan keris disimpan.
Sehari-hari bangunan ini ditunggui seorang wanita yang sudah tak haid
lagi. Dari sini pula, ternyata, sesajen upacara diambil. Dan kadangkala
Mak Loh juga bertugas menjaga bangunan tersebut. “Jaganya sih giliran,
tapi harus wanita yang sudah tidak haid,” ujar Mak Loh.
Djadja Sutedja, sang kuncen, keluar pertama kali. Membawa anglo kecil
berisi kemenyan terbakar, ia berjalan paling depan. Di belakangnya,
lelaki yang dianggap tetua kampung mengiringnya dengan membawa tampah
berisi lemareun.
“Itu sesajen untuk Eyang Singaparna,” ujar Kasadayana sambil
memperinci lemareun yang antara lain: sirih pinang, kapur, gambir,
tembakau, dan daun saga.
Konon Eyang memang suka, alias punya hobi makan sirih. Sambil terus
berkisah Lukanta tegak berdiri, sementara yang lain-lain sudah ada yang
berjalan ke luar. Bertelanjang kaki, dan menyandang sapu lidi, mereka
menuju makam Eyang Singaparna itu. Berbaris satu-satu.
“Sekarang kami akan membersihkan makam dengan sapu ini,” ujar Kasadayana, lalu lenyap di belokan.
Para lelaki yang mengenakan baju putih-putih itu kemudian menempuh
jalan yang sempit, berbelok tajam, dan menanjak. Memasuki makam seorang
diri, di tengah bau dupa yang keras, kuncen melakukan unjuk-unjuk
meminta izin kepada Eyang Singaparna sembari menghadap ke arah barat.
Kuncen merupakan orang terakhir yang meninggalkan makam. Dan kini
masjid kembali didominasi warna putih. Para pengikut upacara dengan
jubah putih mereka kembali duduk, setelah menyimpan sapu lidi di
para-para rumah ibadah itu.
Pemandangan selanjutnya: lewat jendela yang sempit, ratusan tumpeng
yang berisi nasi dan lauk pauk serta buah-buahan mengalir masuk, dan
mengalir ke hadapan tuannya masing-masing. Tumpeng-tumpeng itu disiapkan
oleh kaum perempuan. Dan perempuan tidak mereka bolehkah untuk ke
masjid, itulah sebabnya.
Banyak keunikan di Kampung Naga. Seperti aksitektur rumah-rumah
warga. Rumah-rumah itu tegak disangga kerangka utama dari tiang-tiang
kayu. Berukuran masing-masing sekitar 10 x 10 cm, jumlah tiang utama
pada sisi bangunan yang memanjang selalu lima buah. “Untuk memenuhi
persyaratan lima katimbang,” ujar sang kuncen.
“Dari nenek moyang kami dulu sudah begitu,” katanya.
Dinding rumah rata-rata terbuat dari anyaman bambu. Terdapat dua
jenis anyaman. Pertama kepang, bentuknya seperti anyaman gedeg di Jawa
Tengah. Kedua anyaman sasag.
Menurut Djadja, setiap rumah memiliki kolong. Antara permukaan tanah
dan lantai berfungsi mengatur suhu dan kelembaban udara. Tapi ada pula
kegunaan lain. “Kami di sini menyimpan alat-alat pertanian, dan juga
ternak,” ujar Djadja.
“Yang khas dari arsitektur Kampung Naga adalah atapnya,” kali ini
kata Kasadayana. Atap rumah dilapisi ijuk. Sehingga menyerupai tanduk.
“Orang menyebutnya macam-macam,” ujar Kasadayana, “gapit, cagak gunting,
ada pula yang menyebut capit hurang.”
Kenapa begitu, sebab bumi dan langit dan semua isinya, termasuk
penghuni rumah, merupakan kesatuan jagat raya. Nah, karena itu semua
warga harus menggunakan alam.
“Itu warisan leluhur. Kami tak berani menggantinya dengan genting,
meskipun mudah didapat di sekitar kampung,” ujarnya, yang baru tiga
tahun lalu memperbaiki rumahnya.
Pada prinsipnya, ruang di rumah Kampung Naga terbagi dalam tiga
bagian: depan, tengah, dan belakang. Menurut Djadja, pembagian itu
sesuai dengan pandangan orang Naga terhadap dunia: dunia atas, tengah,
dan bawah. Bagian depan rumah digunakan untuk menerima tamu, dikenal
sebagai daerah pria. Seorang tamu harus dihormati.
Ruang tengah atau tengah imah merupakan daerah netral, bisa digunakan
pria atau wanita. Kegiatan selamatan, meletakkan jenazah sebelum
dimakamkan, bermain bagi anak-anak dilakukan di sini. Di tepi tengah
imah terletak atau kamar tidur. Ini bagian rumah yang sakral.
“Anak-anak dilarang bermain di pangkeng.”
Rumah kuncen Djadja Sutedja juga seperti itu, mengikuti adat. Di
ruang yang terbuat dari bilik yang dicat kapur itu terletak sebuah
tempat tidur berkasur. Di atas kerangka kayu yang memanjang terletak
foto Kuncen dan foto anak-anaknya. Pintu penghubung pangkeng dan tengah
imah hanya ditutup sehelai kain. Tak ada daun pintu.
Di bagian belakang rumah terdapat, dapur. Ini kawasan wanita. Lelaki
hanya diperkenankan masuk untuk keperluan sekadarnya, seperti mengambil
makanan, misalnya.
“Lelaki dilarang bercakap-cakap di dapur,” ujar Sutedja. “Itu tidak
baik.” Tapi bagian belakang yang benar-benar tabu bagi lelaki adalah
goah atau pandaringan. Tempat penyimpanan padi ini hanya boleh dimasuki
kaum hawa.
“Tempat padi kan tempatnya Dewi Sri. Jadi hanya perempuan yang boleh masuk,” kata Djadja lagi.
Dalam satu hal ada lagi, semua rumah memanjang pada jurusan
barat-timur. Masyarakat Naga tak berani menentang kodrat alam, menurut
Djadja lagi. Arah barat-timur, katanya, adalah arah jalannya matahari.
Dengan begitu pintu masuk berada di sebelah selatan atau utara. Tapi
khusus pintu dapur harus dibikin dari anyaman sasag.
“Selain ketentuan leluhur, bila ada bahaya api di dapur lekas ketahuan,” Djadja memberi penjelasan.
Di Kampung Naga, kedudukan seorang kuncen sangat tinggi. Seperti
dikatakan Kasadayana, kuncen dianggap memiliki kekuatan yang berlebih
dari orang kebanyakan termasuk menjadi penghubung manusia dengan
kekuatan-kekuatan luar, misalnya arwah leluhur.
“Tapi sampai kini, menjadi kuncen lebih dari 20 tahun, saya belum pernah mengalami hal-hal gaib,” ujar Sutedja dengan jujurnya.
Rata-rata mata pencaharian masyarakat Kampung Naga adalah petani dan
perajin. Tak heran jika ekonomi warga kurang berjalan lancar. Kesulitan
ekonomi tak hanya dialami Kasadayana, si kuncen sendiri tak luput.
“Rata-rata kami tidak bekerja sebagai dagang atau kantor,” ujar
Kasadayana, sambil memegang kepalanya yang sudah memutih rambutnya.
Kasadayana menceritakan, pernah kuncen (Djadja) tidak punya uang
untuk membiayai anaknya sekolah. Anak-anak Djadja jumlahnya delapan. Ada
yang di SLTP. Karena terlambat bayar, mereka malu dan tidak masuk
sekolah. Kendati demikian Djadja menolak uluran tangan pemerintah
sewaktu hendak menjadikan Kampung Naga obyek wisata.
“Kata kuncen waktu itu, rezeki yang mengatur Tuhan,” cerita Kasadayana.
Menurut kuncen, adanya tempat wisata akan mengundang maksiat. “Nanti
banyak perempuan berkeliaran di sini,” kenang Djadja yang mendapat
tawaran dari pemerintah menjadikan Kampung Naga sebagai tempat wisata.
Memang, bila Kampung Naga dijadikan obyek wisata, keuangan penduduk
akan membaik. “Tapi apa gunanya uang, jika adat-istiadat rusak?” kata
Djadja, agak sengit.
Dalam pemilihan lurah beberapa waktu yang lalu, Djadja sempat
terpilih menduduki jabatan itu. “Saya menangis. Malah saya akan
mengadakan kenduri jika saya tak terpilih.”
Lho kok begitu? “Kalau jadi pejabat, saya akan terpaksa berbohong.
Menipu kuitansi, misalnya. Wah, ya. Kalau terpaksa, yah, tidak apa-apa,
saya kira,” ujarnya. Ia tersenyum, memperlihatkan giginya yang
besar-besar.bs/ajie